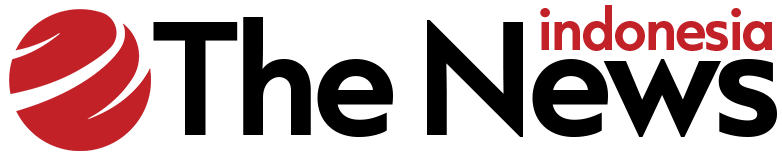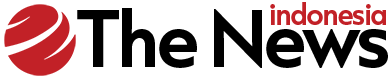Jakarta –
Benturan adat dan pariwisata kembali terjadi di Bali saat perhelatan pesta kembang api di Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, oleh Finns Beach Club dan di saat bersamaan warga menggelar upacara adat. Peran pemerintah dipertanyakan.
Kecaman datang dari berbagai pihak karena kelab itu dinilai tak menghormati umat Hindu yang sedang melaksanakan ritual suci. Finns Beach Club di Canggu, Bali, kembali mencuatkan ketegangan antara masyarakat adat dan pengelola beach club.
Kasus ini berawal dari dugaan pelanggaran nilai adat setempat. Pertunjukan kembang api yang dilakukan oleh Finns Beach Club dinilai melecehkan simbol-simbol keagamaan masyarakat Hindu di Bali, terutama yang berkaitan dengan sosok Ida Sulinggih.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tody Utama, menilai bahwa fenomena itu bukan hanya permasalahan satu pihak yang melanggar adat, tetapi mencerminkan kontestasi ruang dan pluralisme hukum yang semakin kompleks di Bali.
“Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kasus Finns Beach Club ini dari sudut pandang pluralisme hukum dan kontestasi ruang yang sedang terjadi di Bali,” ujar Tody saat wawancara bersama detikTravel, Senin (28/10/2024).
Menurut Tody, gesekan antara masyarakat adat dan industri pariwisata, seperti Finns Beach Club. bukanlah hal baru di Bali. Kasus itu mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara ekonomi, adat, dan kebutuhan publik.
Di satu sisi, desa adat memiliki peraturan lokal atau awig-awig yang kuat, yang secara kultural mengatur masyarakat Bali dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, beach club seperti Finns beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah yang umumnya berfokus pada aspek ekonomi.
Finns Beach Club memiliki izin operasional yang sah dari pemerintah Bali. Sebagai entitas yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, keberadaan beach club ini didukung oleh pemerintah. Namun, desa adat yang merasa terganggu dengan kegiatan Finns menuntut adanya tanggung jawab terhadap dampak budaya yang ditimbulkan.
Menurut Tody, pemerintah perlu menjembatani konflik ini secara bijak agar kepentingan ekonomi dan adat tidak saling bertentangan.
Tody juga menanggapi bahwa sanksi adat bisa menjadi alat negosiasi antara desa adat dan pengelola usaha pariwisata. Misalnya, denda atau upacara permintaan maaf di pura desa adat bisa menjadi solusi damai.
“Sanksi adat dalam konteks ini misalnya pembayaran sejumlah denda dan juga kewajiban untuk melakukan upacara permintaan maaf atau penyucian di pura milik desa,” ujarnya.
Meski demikian, Tody menggarisbawahi bahwa tidak semua pihak luar mau tunduk pada sanksi adat. Tanpa dukungan pemerintah, desa adat tidak memiliki daya paksa yang kuat dalam menerapkan sanksi kepada entitas luar.
“Tanpa dukungan dari pemerintah, desa adat sulit untuk menetapkan sanksi adat yang punya daya paksa yang efektif,” kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terlibat secara aktif agar sanksi adat dapat ditegakkan dengan efektif. Tody juga mengingatkan bahwa setiap konflik yang melibatkan adat dan industri pariwisata di Bali perlu diselesaikan dengan pendekatan bipartit atau melibatkan mediasi dari pemerintah jika dibutuhkan.
“Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan sendiri, pemerintah bisa bertindak sebagai penengah yang netral untuk mencapai keadilan bagi semua pihak,” kata Tody.
Melalui keterlibatan pemerintah yang proaktif, diharapkan konflik seperti ini tidak lagi berulang di masa mendatang. Apalagi, industri pariwisata di Bali harus terus berkembang, namun tetap dengan menghormati adat istiadat yang ada.
Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang memberikan izin usaha, tetapi juga menjadi penjaga agar kepentingan budaya lokal tidak tersisihkan oleh kepentingan ekonomi semata.
(fem/fem)