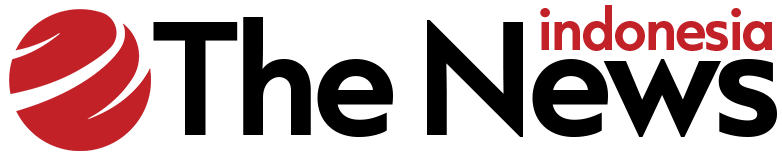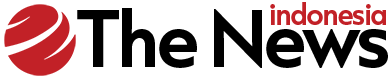Jakarta –
Perpustakaan Batu Api di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat awalnya tidak hanya menyimpan buku. Tempat itu, juga rumah bagi audio (musik) dan video (film) dari seluruh dunia dengan berbagai genre, mulai dari jazz hingga dangdut.
Cahaya matahari menembus tumpukan buku dibalik jendela dari bangunan yang tampak tidak terlalu besar, namun mampu menyimpan ribuan koleksi buku, perpustakaan Batu Api.
Saat detikJabar mengunjungi perpustakaan ini, Selasa (8/10/2024), terdengar alunan musik dari sudut ruangan, seakan menyihir suasana menjadi lebih nyaman. Tumpukan buku yang disampul rapi seolah mengucapkan selamat datang.
Si pemilik, Anton Solihin, duduk di sudut ruangan, bergelut dengan laptopnya dikelilingi tumpukan buku. dia membangun perpustakaan Batu Api sejak 1 April 1999.
|
Perpustakaan Batu Api di Jatinangor. Foto: Asy Syifa Ramadhani Imam
|
Anton menceritakan kendati secara visual tempat itu penuh akan buku, ia justru memulai perjalanannya dengan ketertarikan akan musik.
“Awal itu minatnya musik, rekaman kaset, piring hitam. Dulu kan suka nongkrong di Cihapit, buku belakangan aja. Bukunya harus kelihatan karena ini di tengah kampus, supaya keliatan interaktual,” ujar Anton.
Ya, perpustakaan yang berada di Jl Raya Jatinangor No 142 A, Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, di tengah kawasan yang dihuni ribuan mahasiswa dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya.
Dulu, perpustakaan ini rutin melakukan beragam kegiatan, seperti pemutaran film setiap minggu dari tahun 2001 hingga 2019. Selain itu, Anton juga mengadakan diskusi buku bersama organisasi kampus. Ia juga menghadirkan pembicara dari kalangan penulis hingga sejarawan.
Sayangnya, kegiatan tersebut terhenti setelah Covid-19 melanda dan belum dilanjutkan hingga saat ini. Ia menyampaikan, saat ini kegiatan serupa sudah banyak dilakukan.
Pengunjung Jarang yang Baca Buku
satu keresahan Anton selama mengelola perpustakaan itu. Kendati banyak mahasiswa yang datang, namun hanya sedikit mahasiswa yang datang hanya untuk membaca buku.
“Dari 100 paling 5% yang datang untuk baca, sisanya itu dulu untuk tugas kuliah. Nah kan sekarang tugas kuliah banyak pakai AI,” kata Anton.
Pria yang hobi membuat kliping ini menggunakan kata ‘warung’ yang merujuk pada pustaka Batu Api ini. Bukan tanpa sebab, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Ia tidak memahami sama sekali teknis dari perpustakaan. Meski begitu, ia tetap menunjukkan keseriusannya dalam membangun perpustakaan ini.
“Saya bukan anak jurusan perpustakaan, kategorisasi segala macem, saya tidak peduli. Sampai sekarang masih acak-acakan. Tapi kalau konten saya serius. Bahan yang sekiranya orang susah nyari, saya betulan simpen,” ujarnya.
Anton juga sering berdiskusi dengan para pengunjung. Mulai dari membahas buku atau rekaman yang tersedia, hingga berkonsultasi terkait tugas kuliah.
Seperti yang disampaikan Salman (21), seorang mahasiswa yang sudah beberapa kali berkunjung ke perpustakaan Batu Api. Tidak hanya datang untuk membaca buku, ia juga mencari bacaan sebagai tuntutan tugas kuliah.
“Buku yang aku cari, terutama soal politik atau budaya lebih lengkap dibandingkan perpustakaan lain. Bang Anton juga bisa diajak diskusi, soal ketersediaan buku atau referensi topik yang sedang dibutuhkan,” kata Salman sambil menggenggam sebuah buku.
Hingga saat ini, tidak tahu pasti jumlah buku, rekaman video maupun audio yang ada di perpustakaan ini. Saat awal dibangun, sudah ada sekitar 4.500 buku. Sekarang, belasan ribu rekaman juga dikoleksi oleh Anton. Ia juga membagikan rekaman yang ada secara gratis.
Jika ingin menjadi anggota dari perpustakaan Batu Api, harus mendaftarkan diri dengan biaya Rp 20 ribu. Sementara itu, biaya sewa buku selama seminggu dibanderol Rp 5 ribu.
Digitalisasi Tidak Membantu Tingkatkan Minat Baca
Keresahan lain yang dirasakan Anton adalah tidak ada pengaruh digitalisasi buku atau pun novel. Dia membandingkan kondisi saat masa orde baru dan masa kini. Dulu, saat orba dengan semua hal diseragamkan, mulai dari tontonan hingga pemikiran, orang-orang berusaha untuk ‘berbeda’. Kini di era digital yang penuh kebebasan, banyak yang memilih untuk tetap ‘seragam’.
“Zaman Orde Baru kita semuanya dibuat seragam, tontonannya sampai apa yang dipikirkan seragam. Tapi kita berusaha untuk menjadi berbeda. Sekarang saya justru lihat, orang harusnya punya imajinasi tak terbatas, tapi banyak yang jadi seragam. Jadi kalau dibilang ada perubahan gara-gara digital, ternyata enggak juga,” kata dia.
Tidak lagi sekedar hobi, mengoleksi buku dan rekaman seakan menjadi jalan hidupnya. Perpustakaan ini tetap eksis di tengah digitalisasi dan meningkatnya harga buku di pasaran.
“Sudah tidak bisa disebut hobi saja karena sudah 25 tahun. Ternyata saya bisa hidup dari sini,” kata dia.
(fem/fem)