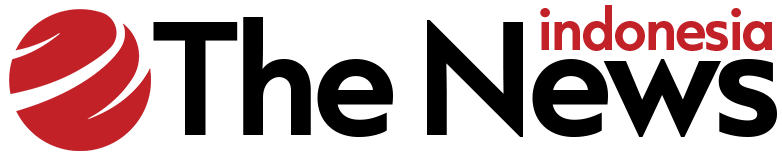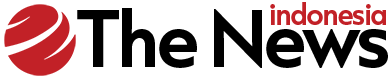Jakarta –
Hampir 200 tahun yang lalu, Matahari tampak seolah-olah berubah warna menjadi aneh, menandai dimulainya periode dua tahun cuaca dingin yang aneh di seluruh dunia.
Para ilmuwan telah lama percaya bahwa efek aneh itu disebabkan oleh letusan. Namun, mereka tidak pernah dapat menentukan gunung berapi mana yang bertanggung jawab atas hal ini.
Diketahui bahwa ‘letusan misterius’ itu mengakibatkan peristiwa pendinginan singkat dan tajam yang terjadi antara tahun 1831 hingga 1833 M, yang menurunkan suhu rata-rata sekitar 1°C.
Komposer Jerman Felix Mendelssohn menulis ini saat bepergian melalui Pegunungan Alpen pada musim panas tahun 1831: “Cuacanya suram, hujan turun lagi sepanjang malam dan sepanjang pagi, sedingin di musim dingin, sudah ada salju tebal di bukit-bukit terdekat.”
Pada Agustus 1831, muncul pula laporan dari seluruh dunia, termasuk China, Eropa, AS, dan Karibia, tentang Matahari yang tampak biru, ungu, dan hijau.
Fenomena ini kemungkinan disebabkan oleh debu dan gas vulkanik yang menyebarkan sinar Matahari dengan cara yang tidak biasa.
Ada beberapa spekulasi bahwa letusan tersebut terjadi di gunung berapi Babuyan Claro di Filipina atau letusan Ferdinandea di dekat Sisilia, tetapi penelitian baru telah mengungkap penyebab baru.
Para ilmuwan di University of St Andrews di Skotlandia telah mengumpulkan bukti kuat bahwa letusan gunung berapi tersebut berasal dari kaldera Zavaritskii di pulau tak berpenghuni Simushir, bagian dari Kepulauan Kuril di Timur Jauh Rusia, tidak terlalu jauh dari Jepang.
Mereka mencapai kesimpulan ini melalui analisis geokimia sampel inti es, yang mengungkapkan ‘kecocokan sidik jari yang sempurna’ dari endapan abu.
“Kami menganalisis kimia es pada resolusi temporal yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan kami untuk menentukan waktu pasti letusan pada musim semi-panas 1831, memastikan bahwa letusan tersebut sangat eksplosif, dan kemudian mengekstrak pecahan-pecahan kecil abu,” kata Dr. Will Hutchison, penulis utama studi dari School of Earth and Environmental Science di University of St Andrews, dikutip dari IFL Science.
“Menemukan kecocokan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan kerja sama yang ekstensif dengan rekan-rekan dari Jepang dan Rusia, yang mengirimkan sampel yang dikumpulkan dari gunung berapi terpencil ini beberapa dekade lalu,” sambungnya.
Disebutkan Hutchinson, momen di laboratorium ketika mereka menganalisis dua abu secara bersamaan, satu dari gunung berapi dan satu dari inti es, adalah momen ‘eureka’ yang sesungguhnya.
“Saya tidak percaya angka-angkanya identik. Setelah ini, saya menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki usia dan ukuran letusan dalam catatan Kuril untuk benar-benar meyakinkan diri sendiri bahwa kecocokan itu nyata,” tambah Hutchison.
Para peneliti mengatakan bahwa pekerjaan mereka menyoroti kekuatan letusan gunung berapi dan potensinya untuk memengaruhi kehidupan di Bumi. Gunung berapi dapat berdampak signifikan terhadap iklim dengan melepaskan gas dan partikulat ke atmosfer, yang menyebabkan efek pendinginan jangka pendek dan, dalam beberapa kasus, berkontribusi terhadap pemanasan jangka panjang.
Misalnya, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 di Filipina mengeluarkan awan sulfur dioksida terbesar yang pernah diukur, yang menyebabkan suhu global turun sekitar 0,5°C selama satu hingga tiga tahun.
Jika letusan lain seperti tahun 1831 terjadi hari ini, itu akan menyebabkan kekacauan yang cukup besar. “Ada begitu banyak gunung berapi seperti ini, yang menyoroti betapa sulitnya memprediksi kapan atau di mana letusan berkekuatan besar berikutnya akan terjadi,” tambah Dr. Hutchison.
“Sebagai ilmuwan dan sebagai masyarakat, kita perlu mempertimbangkan cara mengoordinasikan respons internasional ketika letusan besar berikutnya, seperti yang terjadi pada tahun 1831, terjadi,” pungkasnya.
(rns/rns)