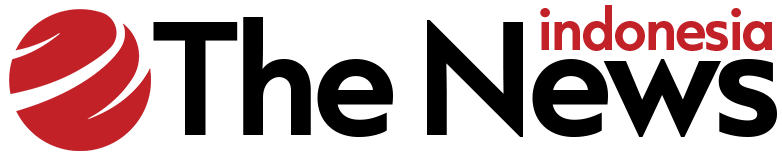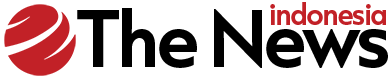Jakarta –
Reog Ponorogo adalah sebuah tradisi yang tak hanya sebagai hiburan rakyat. Konon, tradisi itu punya unsur magis yang kuat dan berawal sebagai sindiran untuk Majapahit.
Para pemain reog punya tugas masing-masing, mulai dari warok, barongan, dadak merak, jathil, sampai bujang ganong.
Tari ini identik dengan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lantas, bagaimana awal mula diciptakannya seni tradisi ini? Dalam Buku Antologi Cerita Rakyat Jawa Timur yang disusun Balai Bahasa Surabaya 2011, Sumono Sandy menjelaskan asal-usul reog.
Sandy mengatakan reog sudah ada sejak zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit sempat berjaya di tangan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Namun pelan-pelan, kerajaan ini mengalami kemunduran.
Lunturnya kewibawaan dan kekuatan Kerajaan Majapahit makin dirasakan di era Raja Bre Kertabumi, raja terakhir Majapahit. Ia tak mampu menjalankan roda pemerintahan seperti raja-raja sebelumnya karena terlalu tunduk kepada permaisurinya yang cantik.
Para pembantu Bre Kertabumi merasa gelisah karena keadaan di dalam istana semakin kacau. Mereka khawatir tentang masa depan Kerajaan Majapahit. Namun karena kuasa sang raja yang terlalu besar, pembantunya tak dapat lagi memberi masukan.
Bahkan, saran dari penasihatnya pun tak lagi didengarkan. Bre Kertabumi lebih senang mendengar pendapat permaisurinya. Salah satu penasihat Bre Kertabumi, Ki Ageng Ketut Suryo Alam termasuk salah satu yang juga merasakan kegelisahan dan kekhawatiran tentang kelangsungan Kerajaan Majapahit.
Kekhawatirannya beralasan. Sebab, roda pemerintahan tidak lagi dikomandoi dengan benar. Ia pun sudah berusaha menasihati sang raja agar tak terlalu mendengarkan permaisurinya. Namun, Bre Kertabumi bergeming.
“Karena merasa kehadirannya sudah tidak ada gunanya, Ki Ageng Ketut Suryo Alam pun menyingkir dari lingkungan istana Kerajaan Majapahit,” jelas Sandy.
Ki Ageng Ketut Suryo Alam menganggap Prabu Bre Kertabumi sudah jauh dari tatanan moral kerajaan. Sandy meyakini penyimpangan moral inilah yang kemudian menghancurkan Kerajaan Majapahit.
“Kebijakan politik Majapahit yang seharusnya dipegang sang raja, pada waktu itu nyatanya dikendalikan permaisurinya sehingga banyak keputusan dan kebijakannya yang tidak benar dan tidak sesuai tatanan peraturan kerajaan,” tutur Sandy.
Setelah angkat kaki dari istana, Ki Ageng Ketut Suryo Alam pergi ke Desa Kutu di wilayah Wengker. Ia mendirikan sebuah padepokan olah kanuragan dan kesaktian, serta mengajari muridnya menjadi seorang prajurit yang bersifat ksatria dan gagah perkasa.
Prinsip yang diyakininya adalah prajurit harus taat kepada kerajaan dan punya kesaktian untuk membela kerajaannya. Untuk dapat memiliki kesaktian, Ki Ageng Ketut Suryo Alam tak memperbolehkan muridnya berhubungan dengan wanita.
Jika dilanggar, kehilangan kesaktian akan menjadi konsekuensinya. Didikan Ki Ageng Ketut Suryo Alam berhasil. Banyak muridnya yang menjadi seorang prajurit bersifat ksatria. Padepokannya juga menjadi populer dan dikenal di berbagai daerah.
“Ki Ageng Ketut Suryo Alam kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu atau Ki Demang Kutu karena padepokannya berada di Desa Kutu,” ungkap Sandy.
Meskipun sudah hengkang dari dalam istana dan sibuk mengajar kanuragan, Ki Ageng Kutu tak pernah berhenti memikirkan kondisi Kerajaan Majapahit. Setiap malam setelah mengajar murid-muridnya, ia kemudian merenung dan berpikir di tempat persembahyangannya.
“Menurut pikirannya, Kerajaan Majapahit harus diingatkan bukan lagi dengan kata-kata dan nasihat. Oleh karena itu, ia terus memikirkan cara dan strategi untuk melawan Kerajaan Majapahit yang dianggapnya telah jauh menyimpang dari tatanan keprajan itu,” kata Sandy.
“Menurutnya (Ki Ageng Kutu), perlawanan dengan senjata dan peperangan tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya akan menimbulkan penderitaan di kalangan rakyat. Di samping itu, dari segi kekuatan prajurit, murid-muridnya tentu akan mudah ditaklukkan oleh bala tentara Majapahit yang jumlahnya jauh lebih banyak,” sambungnya.
Ki Ageng Kutu kemudian memikirkan cara lain untuk melawan Majapahit tanpa adu fisik tapi tetap tepat sasaran. Berhari-hari ia merenung dan berpikir, hingga muncul pikiran untuk melakukan perlawanan secara psikologis berupa kritikan yang dilayangkan lewat kesenian.
Dengan berbekal pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi penasihat di Kerajaan Majapahit, ia paham betul kondisi dalam pemerintahan dan istana. Ditambah keahlian murid-muridnya, Ki Ageng Kutu akhirnya menciptakan drama tari yang disebut reog. Kesenian ini digunakan untuk menggambarkan keadaan kerajaan Majapahit, menjadi sindiran atau satire sekaligus mempunyai makna simbolis.
Ki Ageng Kutu berperan sebagai tokoh warok. Dalam drama tari reog, warok dikelilingi murid-muridnya. Hal itu menggambarkan fungsi dan peranan sesepuh masih tetap diperlukan dan harus diperhatikan dalam sebuah tata pemerintahan.
“Pelaku dalam drama tari reog adalah singo barong yang mengenakan bulu merak di atas kepalanya. Tokoh singo barong merupakan sindiran terhadap kecongkakan, atau kesombongan sang raja yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari para penasihat kerajaan,” ungkap Sandy.
Penari kuda atau jathilan yang diperankan seorang laki-laki yang lemah gemulai dan berdandan seperti wanita menggambarkan hilangnya sifat keprajuritan Kerajaan Majapahit. Para prajurit Kerajaan Majapahit dianggap sudah tidak berdaya.
Tarian penunggang kuda yang aneh menggambarkan ketidakjelasan peranan prajurit kerajaan, ketidakdisiplinan prajurit terhadap rajanya. Namun, raja berusaha mengembalikan kewibawaannya kepada rakyat yang digambarkan dengan penari kuda yang berputar-putar mengelilingi sang raja.
________________
Baca artikel selengkapnya di detikJatim
(wkn/wkn)